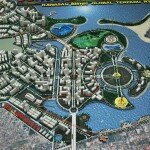Sejumlah proyek yang mengatasnamakan ‘revitalisasi’ makin marak. Contoh revitalisasi Lapangan Karebosi, Pantai Losari, kawasan Benteng Somba Opu, dan, yang terakhir, rencana revitalisasi Sungai Tallo. Apa dan bagaimana penggunaan istilah ‘revitalisasi’ dari sudut pandang arsitek/perancang kota?
Program revitalisasi yang kian marak di Makassar telah menghasilkan proyek fisik baru dari bangunan/kawasan, seperti pada proyek reklamasi anjungan Pantai Losari, Lapangan Karebosi, Benteng Somba Opu, Benteng Fort Rotterdam, dan menyusul Pasar Terong—yang beredar kabar, yang akan berganti nama menjadi Grand Mall Terong. Terakhir, dan sementara dilakukan studi kelayakan berdasarkan kabar yang beredar di media massa maupun online, adalah revitalisasi Sungai Tallo sebagai sarana transportasi air sebagai bagian pengembangan daerah pesisir (waterfront city).
Revitalisasi, menurut Muhammad Danisworo, merupakan upaya menghidupkan kembali suatu kawasan yang mengalami kemunduran/degradasi. Proses ini mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial, kemudian pendekatan revitalisasi harus juga mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan—yang meliputi kesejarahan, makna ruang, keunikan lokasi, dan citra tempat. Dengan demikian, rupanya, proyek revitalisasi bukan semata menitikberatkan pada segi fisik semata.
Jika melihat hasil dari beberapa proyek revitalisasi di Makassar, tampak pada segi perbaikan fisik saja. Sehingga niat baik tujuan revitalisasi tidak tercapai. Malahan sebaliknya, ‘devitalisasi’-lah yang berlangsung. Istilah devitalisasi merujuk pada segala upaya/usaha yang ada mematikan fungsi utama yang seharusnya tetap ada dan berkembang. Dengan begitu, berbagai aspek kehidupan tidak sinergis, sekadar menggelar fragmentasi keindahan yang ‘bisu’. Sedangkan aktivitas dan dinamika ruang yang hidup hanya meninggalkan bekas dan kenangan saja.
Lapangan Karebosi menjadi contoh nyata untuk ini. Dari berbagai sumber historis, lapangan ini sangat penting sebagai ruang bersama utama warga Kota Daeng. Segala kegiatan berlangsung di ruang ini. Tapi, dengan alasan sering banjir dan rawan tindakan kriminal, lapangan ini direvitalisasi. Sekarang, bisa dirasakan, segala interaksi sosial dan budaya, berikut aktivitas ekonomi skala kecil yang berlangsung di dalamnya, ikut hilang. Semua kini berganti dengan kegiatan ekonomi skala besar. Karebosi kini menjadi pusat perbelanjaan, berpagar teralis besi, dan dijaga satpam.
Revitalisasi Masyarakat
Lantaran terlalu mengedepankan aspek fisik, akhirnya aspek manusia terlupakan. Proses perencanaan yang menjadikan manusia sebagai subjek yang aktif dan dinamis selalu alpa dalam cara pandang ini. Padahal agenda revitalisasi pada bangunan dan kawasan tersebut pun juga harus mampu tercerap oleh masyarakatnya—yang dengan demikian, masyarakat dalam melakukan proses ini sepantasnya terlibat penuh, baik dari awal sampai mampu melanjutkannya secara mandiri. Keterlibatan di sini bukan sekadar ‘keikutsertaan-palsu’ atau untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya kata ‘partisipasi’ semata. Namun, berdasarkan Danisworo, suatu keterlibatan yang mendukung dengan memahami proses revitalisasi yang di dalamnya akan terkuak pengetahuan aspek kesejarahan siklus hidup yang terkandung di kawasan tersebut, atau nilai-nilai berharga yang dimiliki hingga apa yang perlu warga lakukan saat ini dan nanti.
Karena itu, Danisworo lewat sebuah weblog menyarankan, mekanisme untuk melibatkan mereka perlu dipersiapkan dengan jelas dan konteks kekinian. Perlu dicatat, masyarakat yang terlibat bisa jadi tidak hanya yang berada di kawasan revitalisasi. Mereka yang memiliki hubungan emosi atau kepedulian dengan tempat tersebut akan menuntut haknya sebagai orang yang perlu dilibatkan pula.
Pada kasus revitalisasi Pantai Losari, dalam diskusi dengan berbagai kalangan, Willy Ferial, penyiar radio kawakan Makassar, menyebut bahwa penggunaan anjungan sebagai tempat pertunjukan musik menurutnya tidak sesuai dengan keberadaan rumah sakit yang tepat berada di depannya.
Hal ini menunjukkan betapa pemerintah dan perencana belum mengakomodir kebutuhan kepentingan warga atas dasar kepemilikan ruang bersama tersebut. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek hanya dianggap sebagai slogan formalitas di saat pertemuan bersama dengan pemerintah. Padahal, ketika warga dijadikan basis pijakan ruang, tentunya akan lebih bisa memberikan pemahaman ruang secara utuh kepada pemerintah dan perencana, yang tentu saja berpeluang besar menyentuh segala dimensi kehidupan yang ada di dalamnya. Proses revitalisasi pun akan hadir sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan kebutuhan politis yang selalu bersembunyi di balik atas nama warga.
Melibatkan warga sebagai subjek merupakan usaha mengakui dan memberi ruang bagi pengetahuan yang mereka miliki. Setelah sekian lama, warga hanya menjadi obyek penataan demi kerapian dan keindahan semata. Pelibatan totalitas akan mengembalikan dan menyadarkan kembali warga sebagai pemilik dan pelaku atas kota ini. Merekalah yang memahami betul siklus ruang yang ada dan siasat-siasat bertahan dalam siklus tersebut. Dengan melibatkan wargalah kota dapat selaras dengan kebutuhan penghuninya. Ini tentunya akan mengurangi keraguan terhadap rasa memiliki kota ini dan itu lebih baik ketimbang memimpikan kota ini sejajar dengan kota dunia lainnya.
Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan, dengan mengutip Danisworo, dapat terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang bisa meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial warga, bukan semata membuat tempat yang sedap dipandang mata. Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri.[]
(Muh. Cora, @muchcora, penggiat Arsitek Komunitas Makassar)